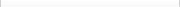BY: Asvin Ellyana
Bahasa adalah jendela untuk melihat realitas dunia. Ungkapan ini mungkin tepat untuk menggambarkan perjalanan ke "negeri tirai bambu". Bahasa Inggris yang konon menjadi bahasa dunia, teryata tak serta merta mampu membuat komunikasi antar anak bangsa menjadi lancar. Inilah yang ditemui penulis sepanjang awal perjalanan.
Sebuah pertistiwa yang tak terlupakan terjadi dalam perjalanan udara dari Jakarta menuju Beijing. Siang itu, pramugari pesawat China Southern dalam bahasa Mandarin menawarkan minuman. Karena bosan telah minum jus jeruk, penulis meminta susu kepada sang pramugari. "Milk please…" begitu pinta saya kepada pramugari.
Kedua pramugari rupanya tak mengerti dan saling pandang mendengar permintaan saya. Dengan suara lebih lantang, saya ulangi permintaan minum susu. Sangat mengagetkan saya karena jawaban salah satu pramugari kepada saya adalah, "No, sory no beer here".
Wah, dalam hati saya marah dan tersinggung, mana mungkin saya yang seorang muslim dengan mengenakan penutup kepala meminta bir? Namun, kemarahan berganti menjadi rasa geli luar biasa mengetahui sang pramugari memaknai "milk" menjadi "beer"...
Kendala bahasalah yang membuat sang pramugari seolah mendengar saya meminta bir. Akhirnya, setelah menunjuk kotak susu yang saya mau, barulah sang pramugari mengerti permintaan saya. Bagi saya, ini pertama kali dalam hidup saya, saya dikira ingin minum bir. Sungguh, tak akan terlupakan.
Namun, tak semua batasan bahasa menjadi halangan berkomunikasi selama di negeri orang. Malam itu, Rabu, 2 November 2011, saat makan malam di sebuah restoran di kota Kashgar, selain makanan khas, kami juga disuguhi sajian musik khas daerah ini. 3 pemain musik memainkan irama yang menyerupai irama padang pasir lengkap dengan nyanyian ala arab. Meski terbata dalam berbahasa Inggris, sang pemain musik, yang merupakan warga muslim dari etnis uygur, mencoba berkomunikasi. Ia menanyakan asal Negara kami. Setelah kami jawab bahwa kami dari Indonesia, si musisi langsung menyatakan bahwa ia pernah berkunjung ke Indonesia. Bahkan dengan fasih ia menyebut sejumlah kota di Negara kami, Jakarta, Bandung dan Surabaya.
Komunikasi terbata akibat perbedaan bahasa tentu mempersulit proses jual beli. Namun, di tengah keterbatasan bahasa tak selamanya merugikan. Penulis justru merasa beruntung mendapatkan barang murah justru karena ketidak mengertian akan bahasa yang disebut sang pemilik toko. Siang itu, saat meliput kerajinan tangan di kota Kashgar, penulis tertarik melihat topi khas etnis Uygur. Saat beberapa teman mencoba menawar barang ditemani guide, penulis mencoba mencari di toko lain. Penulis hanya mengajukan angka 2 kepada penjual hingga akhirnya ia bersedia menjual topi khas itu sebesar 20 yuan. Ternyata, teman lain membeli topi serupa seharga 35 yuan bahkan ada yang membelinya dengan 55 yuan. Ternyata ketidakmengertian akan bahasa sang penjual justru menguntungkan, penulis memperoleh harga yang lebih murah disbanding yang lain. Ternyata di balik kendala bahasa ada saja keuntungannya.
Kasghar, 3 November 2011